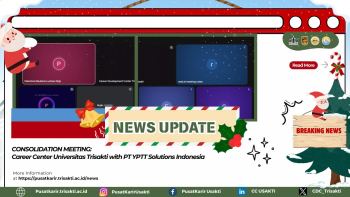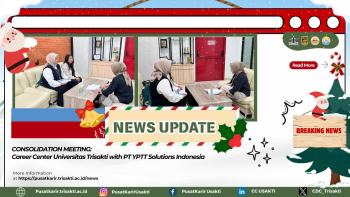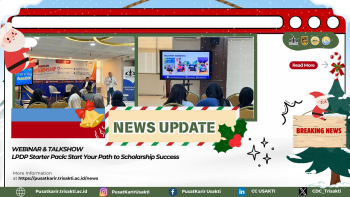LINK AND MATCH, SOLUSI ATAU ILUSI
- 17 Juli 2017

Diskusi mengenai link and macth kembali menghangat terutama dipicu oleh fenomena meningkat pesatnya angka pengangguran terdidik. Dlam kurun waktu kurang dari lima tahun terjadi peningkatan angka pengangguran terdidik sebanyak dua kali lipat, sekarang angkanya telah mencapai 700 ribu orang ( Editorial Media Indonesia, 21 Agustus 2009 ). Banyak yang berpendapat bahwa tingginya angka pengangguran terdidik adalah karena terjadi miss-match antara supply lulusan perguruan tinggi dengan demand dunia kerja. Meskipun hal ini perlu dielaborasi dan diklarifikasi dari kedua sisi yaitu sisi pendidikan tinggi dan sisi dunia kerja.
Konsep link and macth atau saya terjemahkan sebagai hubung-sambung pertama kali muncul diwacana pendidikan di Indonesia sekitar awal tahun 1990-an pada zama Wardiman Djojonegoro menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan saat itu. Perguruan Tinggi dan Industri harus di-link atau dihubungkan dan di macth atau disambung-padankan. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi dapat lebih mudah diserap oleh sektor industri, dan pengangguran terdidik tidak perlu terjadi.
Anatomi mismacth
Jika kita elaborasi, fenomena mismatch memiliki setidaknya dua dimensi. Pertama, secara horisontal mismatch berarti ketidaksesuaian antara bidang/disiplin keilmuan dengan sektor pekerjaan. Kedua, mismatch vertikal yaitu ketidaksesuaian anatara level pendidikan dengan deskripsi dan status pekerjaan.
Mismatch horisontal dapat dimaknai secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hal ini secara kuantitatif kita mungkin sudah mendengar bahwa tingkat kejenuhan penyerapan kerja berbeda-beda untuk masing-masing disiplin keilmuan. Salah satu ukuran dari tingkat kejenuhan penyerapan adalah lama masa tunggu kerja yaitu waktu yang dibutuhkan dari sejak lulus sampai mendapat pekerjaan pertama. Di UI, FKG dan FH adalah yang paling cepat masa tunggu kerjanya yaitu 3 bulan. Secara keseluruhan median masa tunggu kerja untuk lulusan UI adalah 5 bulan (syafiq dan Fikawati, 2008)
Secara kualitatif kita juga menyaksikan banyaknya “pelintas batas” yaitu mereka yang bekerja tidak pada bidang keilmuan mereka. Di Indonesia, banyaknya pelesetan terkait singkatan IPB (Institut Pertanian Bogor), misalnya Institut Pleksibel Banget, sedikit banyaknya mencerminkan banyaknya lulusan IPB yang tidak bekerja di sektor (terkait) pertanian. Data Tracer Study UI (Syafiq dan Fikawati, 2008) menunjukan bahwa sekitar 23% lulusan UI tidak bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya.
Sementara itu mismatch vertikal terjadi ketika seseorang bekerja tidak sesuai dengan level pendidikannya. Misalnya seorang lulusan sarjana S1 mengerjakan pekerjaan yang dapat dikerjakan seorang diploma. Bahkan sekarang ditenggarai bahwa lulusan S2 mengambil alih pekerjaan yang diperuntukan bagi lulusan S1. Menarik bahwa cukup besar jumlah lulusan baru S1 yang langsung melanjutkan studi ke jenjang S2 tanpa interval bekerja terlebih dahulu. Pada lulusan UI, menurut hasil tracer study, persentasenya diestimasi mencapai 20-30% (Syafiq dan Fikawati, 2008). Apakah ini cermin dari kurangnya pekerjaan untuk S1 ataukah meningkatnya kualifikasi dan persyaratan kerja perlu dicermati dan diteliti lebih jauh.
Redefinisi link and macth
Analisis anatomik terhadap fenomena mismatch di atas telah membawa kita pada pertanyaan apakah dengan demikian konsep link and macth masih relevan sebagai solusi bagi persoalan pengangguran terdidik dewasa ini ? Atau link and macth adalah sekedar ilusi yang nampak indah dan sakti tetapi sesungguhnya sama sekali tidak relevan dengan persoalan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Sebagai langkah wal mungkin perlu ditinjau ulang makna link and macth itu sendiri. Jika link and macth dimaknai secara sempit sebagai hubung-sambung antara pendidikan tinggi dan dunia kerja atau kadang lebih sempit lagi dunia industri maka kita hanya akan menjumpai kekecewaan karena tidak akan pernah terjadi perfect macth anatara kedua dunia usaha tersebut seperti telah diuraikan . Oleh karena itu link and macth perlu dimaknai berbeda. Dalam hal ini, Teichler (1999) mengemukakan bahwa universitas haruslah menyiapkan lulusan yang siap menghadapi kehidupan. Maka seorang lulusan perguruan tinggi haruslah link and macth dengan kehidupan, bukan hanya semata-mata dengan persyaratan pasar kerja.
Lulusan perguruan tinggi perlu disiapkan untuk menghadapi kehidupan dengan dibekali kemampuan dan keterampilan melampaui ranah kognitif seperti kemampuan refleksi dan berfikir kritis, kemampuan adaptasi dan fleksibel, serta keterampilan sosial dan organisasional. Schomburg (2009) menekankan pentingnya perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang, bukan memenuhi persyaratan kerja, tapi mampu mengritisi dan menyempurnakan persyaratan kerja itu sendiri.
Sebagai penutup, perlu rasanya menekankan pentingnya dan mendesaknya kebutuhan terhadap data dan informasi yang mutakhir, terbarui, dan sinambung mengenai hubungan antara dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja. Sat ini sistem pemantauan hubungan tersebut belum tersedia secara nasional. Depdiknas dan Depnakertrans sebagai instansi pemerintah yang menangani kedunia itu masih bekerja sendiri-sendiri. Di sisi lain pihak penyelenggara pendidikan tinggi perlu terus menerus meninjau ulang makna kehadirannya ditengah masyarakat dan relevansinya bagi tugas berat mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tengah paradoks dan ironi visi dan misi pendidikan tinggi, sudah saatnya studi dan penelitian di tataran ini ditingkatkan dan dioptimalisasi.
- Penulis : CDC USAKTI